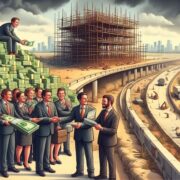JAKARTA – Malam di Pantura jarang benar-benar gelap. Lampu warna warni menggantung di depan deretan warung kopi, memantul di aspal lembab dan badan truk yang lewat pelan. Dari dalam terdengar lagu dangdut, tawa serak, dan bunyi gelas beradu. Dalam statistik resmi, semua ini mungkin rapi masuk kategori jasa restoran, tetapi papan nama warung lebih jujur ketika menuliskan kopi pangku.
Di antara deretan cahaya itu berjalan Sartika, hamil besar, membawa satu tas kecil. Ia baru saja turun dari truk yang mogok, dijadikan kambing hitam dan diturunkan begitu saja. Jalan panjang Pantura bukan panorama wisata baginya, melainkan lorong darurat tanpa alamat pulang. Setelah melewati beberapa warung yang penuh musik dan teriakan, ia berhenti di warung paling ujung yang lebih sepi, milik Bu Maya. Di sana ia beristirahat, melanjutkan hidup hingga melahirkan Bayu, lalu terserap ke dalam ekonomi yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tetapi sangat teratur di pinggir jalan.
Dalam banyak hal, film Pangku bekerja seperti studi kasus lapangan atas statistik kemiskinan dan pasar kerja informal di Indonesia.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, garis kemiskinan per Maret 2025 sekitar 547.752 rupiah per orang per bulan. Di atas kertas, ini batas administratif antara miskin dan tidak miskin. Di dapur rumah seperti milik Sartika, ia adalah perbedaan antara panci yang masih berisi nasi dan panci yang hanya berisi air rebusan mie.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, garis kemiskinan per Maret 2025 sekitar 547.752 rupiah per orang per bulan. (Sumber: BPS)
Sekitar tiga per empat garis kemiskinan adalah pengeluaran makanan, sisanya non makanan. Sedikit saja harga beras naik, tiga per empat jantung anggaran rumah tangga langsung berdebar. Tabungan dan asuransi tetap menjadi kosakata iklan, bukan percakapan di meja makan.
Di film, tekanan itu hadir dalam bentuk ikan yang dibagi di meja makan. Seekor ikan pemberian Hadi jatuh utuh ke piring Bayu. Satu lagi ke piring suami Bu Maya. Satu ekor terakhir dibagi dua untuk Tika dan Bu Maya. Anak lelaki dan lelaki dewasa mendapat bagian terbaik. Dua perempuan yang memasak dan bekerja justru makan paling sedikit. Tabel BPS tidak pernah menulis siapa kebagian kepala dan siapa kebagian ekor, tetapi susunan piring di warung itu terasa seirama dengan angka di atas.
Pertanyaan klasik segera muncul. Mengapa Sartika tidak mencari pekerjaan lain yang lebih terhormat. Di sini data ketenagakerjaan menurunkan nada optimisme. Secara nasional, perempuan mengisi mayoritas pekerjaan di sektor informal, yaitu segala bentuk kerja tanpa kontrak formal dan tanpa jaminan sosial yang jelas.

Perempuan mengisi mayoritas pekerjaan di sektor informal sekitar 63 persen atau 55 juta jiwa, laki-laki 37 persen atau 32 juta jiwa. (Sumber: BPS)
Secara nasional, perempuan mengisi mayoritas mutlak pekerjaan di sektor informal—sekitar 63 persen atau 55 juta jiwa, berbanding 37 persen laki-laki. Dalam pidato pejabat, kondisi ini sering dibungkus dengan istilah manis “jiwa kewirausahaan mandiri”. Padahal dalam praktiknya, sektor informal adalah sekoci bocor bagi jutaan orang yang tidak terserap pabrik dan tidak punya tabungan untuk menganggur. Ketika ekonomi formal bersin, merekalah yang lebih dulu masuk angin. Warung kopi pangku milik Bu Maya hanyalah wujud paling telanjang dari sektor ini, karena modal utamanya bukan mesin atau ruko, melainkan tubuh perempuan itu sendiri.
Kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara laki laki dan perempuan di Jawa Barat ikut menegaskan sempitnya jalan keluar. Layanan pengasuhan anak mahal, jam kerja formal kaku, dan jaminan sosial terbatas. Di atas kertas, perempuan tampak memilih tinggal di rumah. Di layar, pilihan itu lebih mirip saringan. Sartika bekerja malam sambil mengawasi Bayu, mengandalkan kebaikan Bu Maya dan solidaritas rapuh di antara sesama perempuan warung. Di sela itu muncul percakapan kecil antara Bayu dan temannya, yang melahirkan kalimat getir bahwa mencari kantong plastik itu mudah, mencari bapak yang susah. BPS tidak punya variabel untuk mengukur kalimat seperti ini.
Latar ruang yang dipilih film juga bukan kebetulan. Pantura adalah etalase pembangunan jalan dan logistik sekaligus kuburan pelan-pelan bagi banyak rumah tangga tani. Lahan pertanian menyusut, digantikan gudang, pabrik, dan perumahan. Produk domestik bruto bertambah, truk truk melaju dengan kecepatan delapan puluh kilometer per jam. Di tepinya, warung seperti milik Bu Maya menambal biaya sosial yang jarang dibahas. Modernitas melintas di atas roda, kemanusiaan duduk di bangku kayu, menunggu pelanggan.
Di tengah arus ini, Hadi muncul sebagai janji jalan keluar. Ia datang membawa ikan, perhatian, dan rencana hidup yang tampak lebih normal bagi Sartika dan Bayu. Gerobak mie ayam dibuat sebagai simbol kecil harapan. Namun rencana itu tidak pernah benar benar tumbuh. Sebelum usaha berjalan stabil, Anisa, istri sah Hadi yang bekerja di Saudi, datang dan menagih hasil jerih payahnya. Dalam benturan yang tenang tetapi tajam, posisi Tika kembali kalah. Ia meninggalkan rumah dan mendorong gerobak, pulang ke kemiskinan yang lain. Bertahun tahun kemudian barulah kita melihat Bayu, yang dewasa, menjajakan mie ayam. Bukan lompatan dramatis keluar dari kemiskinan, melainkan merangkak pelan dari titik awal ibunya.
Di sini indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan menemukan cerminnya. Di Jawa Barat, indeks-indeks itu menunjukkan bahwa sebagian dari mereka yang sudah miskin justru makin jauh di bawah garis. Jumlah resmi penduduk miskin bisa turun, tetapi bagi keluarga seperti Sartika jalan menuju permukaan tetap curam, dengan langkah yang tersandung sedikit demi sedikit oleh upah rendah, jaring pengaman lemah, dan keputusan orang lain yang punya kuasa lebih besar atas hidup mereka.
Pada akhirnya, kekuatan utama Pangku ada pada penolakannya untuk mendramatisir penderitaan Sartika dengan air mata berlebihan ala sinetron azab. Claresta Taufan memainkannya dengan wajah lelah, bukan wajah sedih. Lelah menghadapi tangan tangan jahil pelanggan, lelah menghitung uang receh yang tidak pernah cukup, lelah berharap pada janji-janji manis yang datang dan pergi secepat truk logistik di luar warung. Reza Rahadian berhasil menangkap jiwa Pantura yang sebenarnya, sebuah wilayah transisi yang keras, di mana modernitas melintas cepat di atas roda truk, sementara kemanusiaan tertinggal di pinggir jalan, duduk di bangku kayu, menunggu seseorang datang untuk sekadar memangku beban hidup mereka sejenak.
Film ini tidak berteriak menyalahkan pemerintah, tidak ada demo buruh, tidak ada orasi panjang. Namun melalui keheningan Sartika, candaan getir Bayu, dan bayang-bayang “data” di balik setiap adegan, Pangku sebenarnya sedang meneriaki kita semua. Ia menggugat kenyamanan yang dibangun di atas punggung-punggung rapuh perempuan di sepanjang jalan Daendels, jalur tua yang dulu dibangun kolonial dan kini menjadi tulang punggung logistik. Sistem berjalan dengan rapi justru karena Sartika tetap miskin. Di atas kertas, ini mungkin hanya pergeseran koma di belakang angka kemiskinan. Di warung kecil di ujung Pantura, itulah horor yang sebenarnya, jauh lebih seram dari film hantu mana pun.